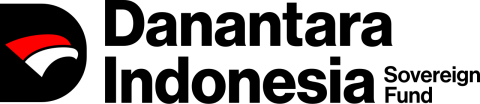Politik dan Birokrasi
( 6554 )Paket Diskon Besar Tiket Pesawat: Strategi Pemerintah Mendorong Mobilitas Nataru
Menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan mengumumkan paket stimulus yang ditujukan untuk menggenjot sektor transportasi dan pariwisata. Program ini berbentuk obral diskon harga tiket pesawat melalui serangkaian insentif fiskal dan non-fiskal. Pemerintah memperkirakan bahwa keseluruhan fasilitas ini dapat menghasilkan penurunan harga tiket pesawat hingga 13 sampai 14 persen bagi konsumen. Diskon ini berlaku untuk pembelian dan periode penerbangan antara 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.
Langkah ini menegaskan upaya pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau selama masa liburan puncak, sekaligus memberikan dorongan vital bagi maskapai penerbangan yang masih berjuang pulih pasca-pandemi. Stimulus sektor transportasi ini dirancang sebagai paket komprehensif yang melibatkan intervensi pada berbagai komponen biaya tiket pesawat.
Pertama, Pemerintah memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah sebesar 6 persen. Dengan tarif PPN normal 11 persen, kebijakan ini membuat penumpang hanya menanggung sisa PPN 5 persen dari total harga tiket. Kebijakan ini secara langsung mengurangi beban pajak yang ditransfer ke konsumen. Selain diskon PPN, maskapai juga mendapatkan keringanan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Untuk pesawat jenis jet mendapatkan diskon fuel surcharge sebesar 2 persen. Untuk pesawat jenis propeller (baling-baling), yang umumnya melayani rute perintis atau jarak pendek, mendapatkan diskon lebih besar, yakni 20 persen.
Selain itu, pemerintah juga memangkas biaya-biaya operasional di bandara, yang sebagian besar dibebankan kepada maskapai dan penumpang. Pemerintah memangkas biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau airport tax sebesar 50 persen. Serta, memotong biaya yang dibebankan ke maskapai berupa biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara, yang dipotong sebesar 50 persen. Untuk melengkapi kebijakan stimulus ini, pemerintah berupaya menekan biaya operasional maskapai secara langsung, harga Avtur (bahan bakar pesawat) diturunkan sebesar 10 persen di 37 bandara strategis di Indonesia. Bahan bakar merupakan komponen biaya terbesar bagi maskapai, sehingga penurunan ini diharapkan langsung terefleksi dalam struktur biaya tiket.
Kebijakan obral diskon tiket ini memiliki dua target utama. Target pertama adalah mengendalikan inflasi dan memastikan masyarakat dapat bepergian tanpa terbebani biaya transportasi yang terlalu tinggi selama periode Nataru. Kenaikan harga tiket pesawat dapat memicu kenaikan inflasi pada sektor jasa dan transportasi. Target kedua adalah akselerasi pemulihan sektor pariwisata domestik. Dengan tiket yang lebih terjangkau, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk melakukan perjalanan domestik, yang secara langsung menggerakkan roda ekonomi daerah-daerah tujuan wisata.
Meskipun paket stimulus ini terlihat menarik, tantangan implementasinya terletak pada pengawasan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh komponen diskon yang diberikan (PPN DTP, fuel surcharge, PJP2U, dan harga avtur) benar-benar diturunkan kepada konsumen dalam bentuk harga tiket yang lebih murah, sesuai dengan target 13-14 persen.
Maskapai dan pengelola bandara harus transparan dalam menghitung dan mencantumkan komponen harga tiket agar publik dapat melihat manfaat diskon tersebut secara jelas. Jika pengawasan lemah, insentif fiskal yang dikeluarkan negara berisiko hanya terserap sebagai margin keuntungan maskapai atau bandara, tanpa manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Cukai Rokok 'Ditahan': Sinyal Perlindungan Industri di Tengah Dilema Kesehatan dan Fiskal
Kabar terbaru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menjadi perhatian utama bagi industri tembakau dan publik. Menteri Keuangan Purbaya secara resmi menegaskan bahwa tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak akan dinaikkan pada tahun 2026. Penegasan ini disampaikan Purbaya usai bertemu dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) pada Jumat (26/9).
Keputusan ini menandai pergeseran signifikan dari tren kenaikan CHT yang rutin diterapkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Purbaya bahkan menyebut bahwa tarif cukai rokok saat ini dinilai terlalu mahal, dan ia sempat mempertimbangkan untuk menurunkannya—meski langkah tersebut belum diambil. Kebijakan menahan kenaikan cukai ini menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, sedang menempuh jalan keseimbangan yang kompleks: antara perlindungan industri tembakau dan kebutuhan fiskal negara yang juga menanggung beban kesehatan masyarakat.
Keputusan untuk tidak menaikkan CHT pada 2026 dapat dipandang sebagai respons pro-industri. Kenaikan cukai yang agresif sering kali dituding menjadi penyebab tertekannya industri rokok legal, yang berdampak langsung pada kestabilan industri dan ketenagakerjaan. Industri tembakau merupakan salah satu sektor padat karya di Indonesia, menyerap jutaan tenaga kerja mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga rantai distribusi. Dengan menahan kenaikan tarif, pemerintah berupaya menjaga daya saing industri, mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), dan memastikan kelangsungan operasional pabrik, terutama yang berskala kecil dan menengah.
Kebijakan Menteri Purbaya ini juga berefek pada jual beli rokok illegal. Argumentasi utama di balik penahanan cukai adalah memerangi peredaran rokok ilegal. Menteri Purbaya secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk menindak tegas peredaran rokok illegal baik secara luring maupun daring yang selama ini merugikan perusahaan legal dan mengurangi penerimaan negara. Harga rokok ilegal yang jauh lebih murah menjadi substitusi bagi konsumen ketika harga rokok legal melambung tinggi akibat kenaikan CHT. Dengan menahan kenaikan, pemerintah berharap dapat mempersempit jurang harga dan menekan insentif bagi pelaku rokok ilegal.
Keberhasilan kebijakan 'cukai ditahan' ini sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menekan rokok ilegal. Janji Menteri Purbaya untuk menindak peredaran rokok ilegal adalah kunci. Penindakan rokok ilegal memerlukan kolaborasi yang kuat antara Ditjen Bea dan Cukai, Kepolisian, hingga aparat pemerintah daerah. Tantangannya adalah kompleksitas jaringan peredaran yang bergerak cepat dan memanfaatkan jalur-jalur tikus, baik di darat, laut, maupun melalui platform digital. Jika penindakan rokok ilegal tidak efektif, yang terjadi justru potensi kerugian ganda: penerimaan negara tidak maksimal (karena tarif tidak naik), sementara industri rokok legal tetap tertekan karena harus bersaing dengan produk ilegal yang murah.
Kesimpulannya, kebijakan tidak menaikkan CHT pada 2026 adalah langkah berani yang diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan industri dan melawan rokok ilegal. Namun, pemerintah wajib memastikan bahwa pilihan ini tidak mencederai komitmen pengendalian konsumsi tembakau dan tidak menciptakan lubang besar pada target penerimaan negara di tengah kebutuhan fiskal yang tinggi.Mengejar Rp60 Triliun: Tantangan Besar Kementerian Keuangan di Balik Janji Menagih 200 Pengemplang Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini melontarkan pernyataan tegas yang menarik perhatian publik sekaligus pelaku usaha. Menteri Keuangan Purbaya secara terbuka menyatakan komitmennya untuk mengejar dan menagih utang pajak dari sekitar 200 wajib pajak besar yang kasusnya telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Total uang negara yang menjadi target penagihan diklaim mencapai angka fantastis, berkisar antara Rp50 triliun hingga Rp60 triliun.
Janji ini, yang disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTA pada Senin (22/9), menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan memastikan keadilan fiskal. Meskipun Kemenkeu telah mencatat keberhasilan penagihan sebesar Rp7,21 triliun hingga pertengahan Oktober 2025, merealisasikan sisa target puluhan triliun rupiah tersebut bukanlah perkara mudah. Upaya ini akan berhadapan dengan berbagai tantangan hukum, teknis, dan operasional yang kompleks.
Tantangan utama dalam eksekusi penagihan utang pajak yang sudah inkracht adalah aspek hukum dan aset. Pertama, status dan lokasi Aset. Meskipun putusan pengadilan sudah final, pengemplang pajak besar seringkali telah menyembunyikan atau memindahtangankan aset mereka jauh sebelum proses hukum selesai. Aset-aset tersebut bisa berbentuk investasi di luar negeri, properti atas nama pihak ketiga, atau aset digital yang sulit dilacak. Menetapkan sita eksekutorial pada aset yang kompleks dan multiyurisdiksi membutuhkan koordinasi internasional dan proses hukum yang panjang.
Kedua, terkait perlawanan hukum pasca putusan. Wajib pajak yang ditagih, terutama dengan nilai utang triliunan rupiah, hampir dipastikan akan melakukan perlawanan hukum lanjutan, seperti mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau gugatan perdata terkait status kepemilikan aset yang disita. Hal ini dapat memperlambat proses eksekusi penagihan hingga bertahun-tahun.
Selain tantangan utama tersebut, juga terdapat tantangan dari aspek kapasitas organisasi Direktorat Jenderal Pajak Penagihan utang pajak skala besar membutuhkan sumber daya dan keahlian khusus yang mungkin belum optimal dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaksanaan penagihan untuk jenis utang apapun adalah proses yang menantang, apalagi terkait utang pajak yang bernilai besar.
Dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni dan keahlian penulusuran asset. Mengejar 200 pengemplang besar memerlukan tim khusus dengan keahlian investigasi forensik, analisis keuangan transnasional, dan pemahaman mendalam tentang skema penghindaran pajak yang canggih. Jumlah penagih pajak yang memiliki kompetensi tinggi di bidang ini seringkali terbatas, sementara kasus-kasus yang ditangani memiliki kompleksitas tinggi.
Lebihlanjut, Kemenkeu membuka peluang penggunaan sanksi ekstrem, termasuk penyanderaan (gijzeling). Meskipun efektif memberikan tekanan, penerapan gijzeling memerlukan prosedur hukum yang ketat dan persetujuan pengadilan. Penggunaan sanksi ini secara masif dapat memicu reaksi balik dari pelaku usaha dan berpotensi menimbulkan isu hak asasi manusia jika tidak dilakukan secara prosedural dan selektif.
Ketegasan Menteri Keuangan patut diapresiasi, namun demikian keberhasilan proses penagihan pajak tidak hanya berada dalam kontrol kewenangan Menteri Keuangan. Seperti, Tidak semua utang pajak yang sudah inkracht dapat ditagih. Dalam beberapa kasus, perusahaan pengemplang telah bubar atau asetnya tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban. Jika dari target Rp60 triliun tersebut, sebagian besar ternyata harus dihapusbukukan (write-off), hal itu dapat menurunkan kredibilitas janji dan target penerimaan pajak. Juga terdapat potensi intervensi dan tekanan politik. Penagihan utang pajak skala besar melibatkan entitas bisnis yang memiliki pengaruh signifikan. Tekanan politik dan upaya intervensi dapat menjadi hambatan besar bagi independensi otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya.
Janji Menteri Purbaya adalah sinyal kuat bagi wajib pajak untuk patuh. Namun, efektivitas realisasinya akan diuji oleh kemampuan Kemenkeu dalam mengatasi labirin tantangan hukum dan teknis di lapangan. Sejatinya kepentingan untuk merealisasikan piutang pajak adalah kepentingan strategis negara. Untuk itu ketegasan Menteri Keuangan perlu terus dikawal dan didukung publik.Mengurai Peluang dan Tantangan BPI Danantara: Dampak Krusial pada Pengelolaan Fiskal
Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi salah satu kebijakan ekonomi paling signifikan selama satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. BPI Danantara, yang berfungsi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) berkapasitas besar, dirancang untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset-aset strategis negara, termasuk tujuh BUMN raksasa seperti Pertamina, PLN, dan bank-bank milik negara, dengan total aset yang dikelola diperkirakan mencapai Rp9.000 triliun.
Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk menciptakan sumber pendanaan investasi non-APBN, mendukung program-program pembangunan prioritas, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Namun, di balik ambisi tersebut, pembentukan entitas super ini memunculkan dualitas risiko dan peluang yang harus dicermati secara mendalam, terutama implikasinya terhadap stabilitas fiskal dan penerimaan perpajakan.
Dari sudut pandang ekonomi makro dan pengelolaan fiskal, BPI Danantara menawarkan beberapa potensi positif jangka Panjang. Pertama, terkait penciptaan nilai asset. Konsolidasi aset-aset BUMN diharapkan dapat menciptakan sinergi dan efisiensi yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas. Pengelolaan aset secara profesional dan strategis oleh BPI Danantara berpotensi menghasilkan return investasi yang tinggi. Peningkatan nilai dan keuntungan ini akan memperkuat fundamental ekonomi dan secara bertahap memperluas basis pajak di masa depan.
Kedua, diversifikasi pendanaan pembangunan. BPI Danantara dapat berperan penting dalam menarik modal asing dan domestik untuk membiayai proyek infrastruktur besar tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN. Dana yang dikelola, termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan alokasi efisiensi anggaran, dapat berputar lebih cepat di sektor riil, mengurangi tekanan pada defisit fiskal, dan membebaskan ruang fiskal APBN untuk kebutuhan belanja sosial.
Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan mitigasi serius, khususnya karena BPI Danantara melibatkan aset vital yang selama ini menjadi penyumbang signifikan bagi kas negara. Terdapat potensi pengurangan penerimaan jangka pendek. Demi menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan modal BPI Danantara, entitas ini atau anak usahanya berpotensi diberikan insentif atau perlakuan khusus di sektor perpajakan. Jika insentif ini berlaku pada BUMN yang sebelumnya merupakan penyetor pajak dan dividen besar, maka APBN dapat mengalami tekanan finansial karena hilangnya sumber penerimaan rutin. Kondisi ini terjadi di tengah kebutuhan anggaran yang tinggi untuk program-program baru dan pembayaran utang jatuh tempo.
Selain itu, risiko salah kelola tetap akan membayangi perjalanan BPI Danantara kedepannya. Pengumuman kasus dugaan korupsi di salah satu BUMN yang direncanakan bergabung ke BPI Danantara menjadi alarm keras terkait isu Good Corporate Governance (GCG). Pengelolaan aset triliunan rupiah membutuhkan integritas dan transparansi tertinggi. Jika terjadi salah investasi atau, yang lebih parah, korupsi di dalam BPI Danantara, kerugian yang timbul akan menjadi beban utang dan tanggung jawab fiskal negara. Kegagalan ini pada akhirnya berisiko ditutup melalui peningkatan penerimaan perpajakan di sektor lain atau menaikkan rasio utang nasional.
Oleh karena itu, pentingnya tata kelola yang baik dan transparansi. BPI Danantara memegang kunci penting dalam masa depan pendanaan pembangunan Indonesia. Keberhasilannya bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu mengeliminasi kerawanan yang ada. Langkah fundamental yang harus dilakukan adalah menetapkan kerangka GCG yang independen dan transparan untuk meminimalisir risiko moral (moral hazard) dan korupsi. Selain itu, perlu adanya kajian fiskal yang cermat untuk memastikan bahwa kebijakan insentif pajak yang mungkin diberikan tidak mengorbankan penerimaan APBN secara drastis dalam jangka pendek, dan bahwa manfaat jangka panjangnya benar-benar mampu menutupi potensi kerugian tersebut.
Dengan manajemen risiko yang hati-hati dan tata kelola yang profesional, BPI Danantara dapat benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, alih-alih menjadi beban fiskal dan penerbit utang baru di masa mendatang.Dana Bagi Hasil: Dilema Keadilan Fiskal dan Pemerataan Pembangunan
Sejak era reformasi, sistem desentralisasi di Indonesia telah menjadi pilar penting tata kelola negara. Pelimpahan sebagian besar kewenangan dari pusat ke daerah mengharuskan Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang memadai untuk memastikan roda pembangunan terus berputar. Inilah cikal bakal lahirnya Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen vital dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
TKD dirancang untuk menutup kesenjangan fiskal antar-daerah dan memastikan setiap wilayah mampu membiayai layanan publik dasar. Di antara berbagai komponen TKD—seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)—terdapat satu instrumen yang memiliki karakteristik unik dan kerap memicu perdebatan: Dana Bagi Hasil (DBH).
Fungsi Krusial DBH dalam Desentralisasi
Pada dasarnya, DBH adalah mekanisme pengembalian sebagian pendapatan negara kepada daerah penghasil. Dana ini dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan APBN yang bersumber dari pajak dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di daerah terkait.
Tujuan utama dari mekanisme ini sangatlah strategis. Pertama, DBH dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, memungkinkan mereka membiayai pelaksanaan kewenangan desentralisasi. Kedua, DBH berfungsi sebagai kompensasi atas dampak eksternalitas negatif yang timbul akibat eksploitasi SDA—seperti kerusakan lingkungan, infrastruktur yang menua, dan perubahan sosial—sehingga dana ini dapat digunakan untuk rehabilitasi atau pembangunan berkelanjutan. Ketiga, dan yang paling fundamental, DBH diharapkan menjadi salah satu pendorong utama pemerataan pembangunan antarwilayah.
Dengan adanya DBH, daerah yang menjadi lumbung pendapatan negara—baik dari sektor migas, mineral, atau penerimaan pajak yang tinggi—dapat memiliki daya ungkit finansial yang kuat untuk mempercepat laju pembangunan daerahnya.
Jerat Ketimpangan: Paradoks DBH
Namun, alokasi DBH yang didasarkan pada prinsip 'daerah penghasil mendapatkan lebih' justru memunculkan dilema fiskal yang tajam: ketimpangan.
Secara inheren, skema DBH memperkuat perbedaan antara daerah yang "kaya" SDA dan yang "miskin" SDA. Daerah dengan cadangan migas dan mineral melimpah otomatis menerima porsi DBH yang substansial. Akibatnya, mereka memiliki keleluasaan finansial yang jauh lebih besar untuk membangun infrastruktur ambisius dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebaliknya, daerah yang minim SDA, meskipun memiliki kebutuhan pembangunan dan tingkat kemiskinan yang tinggi, hanya mendapatkan alokasi DBH yang kecil. Hal ini memperlebar jurang kesenjangan fiskal antar-daerah. DBH, yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan, pada kenyataannya berpotensi memperkuat disparitas, karena alokasinya lebih didominasi oleh faktor kekayaan alam yang distribusinya tidak merata secara geografis.
Jika tidak dikelola dengan bijak, daerah kaya SDA bisa terjebak dalam 'Dutch Disease'—ketergantungan berlebihan pada satu sektor (SDA) dan mengabaikan pengembangan sektor non-SDA—sementara daerah lain terus tertinggal.
Mempertajam Instrumen Pemerataan
Mengingat DBH adalah komponen penting dalam postur APBN, efektivitasnya sebagai motor pemerataan harus terus diuji dan ditingkatkan. Setidaknya terdapat tiga Langkah yang dapat Pemerintah Pusat tempuh agar janji desentralisasi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Pertama, Mengoptimalkan Fungsi Penyeimbang (Equalizer): Peran utama sebagai penyeimbang fiskal harus dibebankan pada instrumen TKD lainnya, yaitu DAU dan DAK. Formula DAU harus dibuat lebih sensitif terhadap indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan kesulitan geografis, memastikan bahwa daerah dengan keterbatasan sumber daya tetap mampu membiayai kebutuhan dasarnya.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas penggunaan. Pemerintah harus memastikan dana DBH benar-benar digunakan untuk investasi produktif, seperti pembangunan infrastruktur vital, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan lingkungan. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah DBH hanya terserap dalam belanja rutin atau proyek yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Terakhir, pemerintah pusat perlu Mendorong Kapasitas Fiskal Mandiri bagi daerah. Daerah harus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Pemda perlu berinovasi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor non-SDA, seperti pariwisata, jasa, dan pengembangan ekonomi kreatif.
DBH adalah manifestasi dari keadilan fiskal: mengembalikan hak daerah atas sumber daya yang dihasilkan. Namun, tanpa penajaman formula dan penguatan instrumen penyeimbang lainnya, DBH akan tetap menjadi pedang bermata dua yang di satu sisi menyejahterakan daerah penghasil, namun di sisi lain berisiko memperparah ketimpangan pembangunan nasional. Sinergi seluruh komponen TKD adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan merata.Program Pengampunan Diperluas
Rekor Baru: Sisa Anggaran Pemerintah Tertinggi Sepanjang Sejarah
Pelaksanaan belanja negara pada 2025 menunjukkan kinerja yang belum optimal, tercermin dari lonjakan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang menembus Rp 303,8 triliun per akhir Mei 2025—tertinggi dalam enam tahun terakhir. Kenaikan SiLPA ini menandakan lambannya penyerapan belanja negara meski alokasi APBN cukup besar.
Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (Core), menilai penumpukan SiLPA di satu sisi adalah bentuk kehati-hatian fiskal untuk menghadapi ketidakpastian global dan potensi seretnya penerimaan negara, terutama dari pajak. Namun ia mengingatkan bahwa dana yang terlalu lama tersimpan berisiko menjadi tidak produktif, mengurangi efektivitas kebijakan fiskal, dan gagal memberikan manfaat langsung yang dibutuhkan masyarakat. Yusuf mendorong pemerintah untuk lebih proaktif menyalurkan dana ke program prioritas agar APBN tetap berfungsi optimal sebagai instrumen pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, melihat lonjakan SiLPA sebagai upaya antisipasi pemerintah menghadapi risiko penerimaan pajak yang lemah, seiring sektor manufaktur—penyumbang sekitar 28% pajak—yang melambat dengan PMI di level kontraksi 47,4 pada Mei 2025. Selain itu, pemerintah memerlukan cadangan tunai untuk membiayai program besar seperti Makan Bergizi Gratis hingga akhir tahun. Bhima juga menekankan SiLPA dapat digunakan untuk menutup pembayaran bunga utang pada kuartal IV, terutama jika defisit anggaran melebar.
Tingginya SiLPA mencerminkan dilema pemerintah antara kehati-hatian fiskal dan lemahnya eksekusi belanja. Meski dapat menjadi bantalan menghadapi risiko eksternal, penyaluran yang lebih cepat dan tepat diperlukan agar APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
KPK Selidiki Dugaan Aliran Dana Rp 2 Miliar
Bansos Pendorong Pertumbuhan Secara Berkelanjutan
Pemberian bantuan sosial (bansos) tidak hanya menjadi solusi
jangka pendek, tetapi dapat berperan sebagai instrusmen penyokong perekonomian
secara berkelanjutan. Ketika kesejahteraan masyarakat menengah bawah meningkat,
maka hal itu akan memberikan efek domino terhadap pertumbuahn ekonomi. Anggota
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengatakan, pemberian bansos
merupakan langkah pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical saat
perekonomian sedang tertekan. Bansos dapat berperan sebagai intrusmen untuk
menegakkan keadilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Orang sering
mengistilahkan bansos itu sebagai biaya (spending). Padahal, bansos adalah
investasi supaya kita (Indonesia) mendapatkan future growth atau bahkan growth
sekarang juga,” kata Arief. Dia mengatakan, bansos menjadi intrusmen negara
untuk memberikan perlindungan sosial dalam jangka panjang. Dalam hal ini bansos
akan berperan menekan angka kemiskinan. “Dalam jangka panjang bansos itu akan
dan harus selalu ada,” imbuh Arief. (Yetede)
Mengendalikan Daya Tarik Eksplorasi Migas
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023